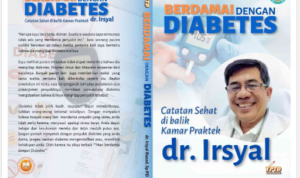Ketika sebuah persoalan muncul, tak jarang orang merasa sedang mengalami penderitaan yang sangat besar. Beban hidupnya terasa sangat menekan seolah sedang memikul beban yang sangat berat. Kemudian, muncul perasaan bahwa ia adalah orang yang mengalami masalah yang paling menderita.

Sebuah pengalaman seseorang yang dekat dekat penulis menggambarkan hal demikian. Berawal dari sebuah kekesalan yang dirasakannya terhadap seorang yang lain. Kekesalan itu kemudian diekspresikan dengan luapan tangis yang histeris. Ia tidak mempedulikan keadaannya ataupun situasi di sekitarnya lagi.
Di sela-sela tangisnya, ia berkata bahwa hidupnya begitu tidak beruntung karena persoalan yang dialaminya. Ia merasa seolah ia memiliki kurangan yang sangat besar yang menyebabkannya menderita seperti yang sedang ia rasakan.
Sesaat kemudian, ia mulai terbawa suasana dan memutar lagu-lagu sedih yang sesuai dengan perasaannya itu. Tentu saja, alunan lagu yang sedih akan semakin membuatnya bersedih. Namun, ia seolah “menikmati” sekali kesedihannya itu. Ia dengan mudah membawa dirinya masuk lebih jauh ke dalam suasana kesedihan yang diciptakannya itu.
Sedih itu Manusiawi
Memang, sebuah keniscayaan bahwa hidup manusia akan selalu mengalami tantangan dan hambatan. Itulah kodrat manusiawi semua insan di dunia ini. Tidak ada seorang pun dapat mengelak dari tantangan dan hambatan yang menghadang tersebut.
Namun, manusia cenderung ingin menjadi seseorang yang sempurna. Tantangan dan hambatan seringkali dianggap sebagai sebuah kesalahan yang tak perlu hadir dalam hidup manusia.
Padahal, sejatinya manusia tidak terbebas dari berbagai tantangan dan hambatan. Hal itu pulalah yang seharusnya menjadi alasan manusia untuk mendekat kepada Pencipta-Nya sebagai satu-satunya Penolong.
Ketika persoalan datang, orang seringkali menjadi lupa diri. Lupa menempatkan diri sebagai pribadi yang seharusnya bersikap pasrah dan berserah kepada kehendak-Nya.
Memang, pada awalnya, persoalan akan tampak mengejutkan bagi seseorang. Akan tetapi, bukankah seharusnya kita tidak “menjerumuskan” diri untuk meratapi hidup akibat persoalan itu terus menerus dan berkepanjangan?
Baca juga: Ketika Rasa Takut Selalu Membayangi
Sikap Takabur Manusia
Sikap histeris, tangisan meraung-raung dan perasaan sebagai penderita merupakan gambaran penolakan, protes dan penghakiman terhadap Sang Pencipta. Orang seperti itu tidak bersedia menerima dirinya apa adanya pada saat itu. Biasanya, muncul tuntutan kepada-Nya, ”mengapa hal ini harus terjadi pada saya?”
Tanpa disadari, sikap sedih berkepanjangan telah membawa manusia pada kesombongan itu. Manusia seolah tidak menerima kenyataan bahwa ia harus melalui tantangan atau persoalan itu dengan kebesaran hati. Bukankah, sejak lama Dia telah berpesan agar manusia menyerahkan segala kehawatiran itu dalam kepasrahan kepada-Nya.
Manusia hanya mampu menuntut sesuatu untuk dirinya sendiri. Di mana penghayatan iman manusia kepada Sang Pemilik Kehidupan?. Sebuah penghayatan iman, seyogyanya menunjukkan suatu kepasrahan diri bahwa Dia akan selalu menyertai umat-Nya.
Sayangnya, manusia seringkali bersembunyi dalam sisi kemanusiawiannya itu. Mereka membela diri dengan mengatakan: “bukankah wajar saya merasa bersedih dan marah?” Tentu saja, tidak ada seorang pun yang melarang seseorang untuk merasa sedih, marah atau perasaan lainnya.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kepasrahan sebagai manusia ciptaan kepada Pencipta-Nya itulah yang dituntut dari setiap insan yang beriman. Iman yang teguh kepada Sang Pencipta, seharusnya menjadi tameng yang memperkuat diri menghadapi persoalan dan tantangan yang menghadang. Bukan sebaliknya, berteriak histeris, menangis meraung-raung dan merasa sebagai orang paling menderita. Sikap demikian menunjukkan diri sebagai seseorang yang tidak mengenal Tuhan.
Mungkin, pada bagian ini, banyak orang belum sampai pada penghayatan yang mendalam mengenai konsep kepasrahan kepada Sang Pemilik Kehidupan. Apa yang diyakini seseorang sebagai iman, mungkin dapat dikatakan masih berada pada tatar terluar pemahaman mereka ketika mereka gagal bersikap ketika menghadapi persoalan.
Bersyukur Sebagai Ungkapan Iman
Para orang tua dahulu sering kali mengajarkan anak-anaknya agar mampu beryukur atas apa yang mereka alami dan terima. Tentu saja ini nasehat yang baik. Namun, kata “syukur” seringkali dianggap sebagai milik orang suci. Nasihat untuk bersyukur kurang atau bahkan tidak dipahami sepenuhnya sehingga dianggap angin lalu saja, bagai angin sepoi-sepoi yang menyapu kulit dan berlalu begitu saja.
Sikap syukur menyiratkan sebuah tindakan menerima keadaan apa adanya sebagai bagian dari rencana-Nya. Tindakan ini disertai upaya untuk keluar dari zona persoalan dengan cara yang bijak seraya memohon kekuatan dari-Nya.
Sebagai pribadi, penulis meyakini bahwa langit tidak selalu biru, dan jalanan tidak selalu rata. Kehidupan pun tidak selalu berjalan mulus. Satu yang pasti telah diyakinkan-Nya bahwa Dia akan selalu menyertai manusia dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya.***
Kunjungi Blog saya: http://www.christpard.com/